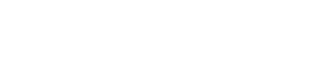Iklan
Pertanyaan
Bacalah teks cerpen berikut ini!
Teks cerpen A
MBOK JAH
Oleh Umar Kayam
Sudah dua tahun, baik pada Lebaran maupun Sekaten, Mbok Jah tidak “turun gunung” keluar dari desanya di bilangan Tepus, Gunung Kidul, untuk berkunjung ke rumah bekas majikannya, keluarga Mulyono, di kota. Meskipun sudah berhenti karena usia tua, dan capek menjadi pembantu rumah tangga, Mbok Jah tetap memelihara hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga itu. Dua puluh tahun telah dilewatinya untuk bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga yang sederhana dan sedang-sedang saja kondisi ekonominya itu.
Gaji yang diterimanya tidak pernah tinggi. Cukup saja. Tetapi, perlakuan yang baik dan penuh tepa selira dari seluruh keluarga itu telah memberinya rasa aman, tenang, dan tenteram. Buat seorang janda yang sudah setua itu, apakah yang dikehendaki lagi selain atap untuk berteduh dan makan serta pakaian yang cukup. Lagi pula anak tunggalnya yang tinggal di Surabaya dan menurut kabar hidup berkecukupan, tidak mau lagi berhubungan dengannya. Tarikan dan pelukan isteri dan anak-anaknya rupanya begitu erat melengket hingga mampu melupakan ibunya sama sekali. Tidak apa, hiburnya.
Di rumah keluarga Mulyono ini, dia merasa mendapat semuanya. Tetapi, waktu dia mulai merasa semakin renta tidak sekuat sebelumnya – Mbok Jah merasa dirinya menjadi beban keluarga itu. Dia merasa butuh tumpangan gratis. Dan harga dirinya memberontak terhadap keadaan itu. Diputuskannya untuk pulang saja ke desanya.
Dia masih memiliki warisan sebuah rumah desa yang meskipun sudah tua dan tidak terpelihara akan dapat dijadikannya tempat tinggal di hari tua. Dan juga tegalan barang sepetak dua petak masih juga ada. Pasti semua itu dapat diaturnya dengan anak jauhnya di desa. Pasti mereka semua dengan senang hati akan menolongnya mempersiapkan semua itu. Orang desa semua tulus hatinya.
Maka dikemukakannya ini kepada majikannya. Majikannya beserta seluruh anggota keluarga – yang hanya terdiri dari suami, istri, dan dua orang anak – protes keras dengan keputusan Mbok Jah. Mbok Jah sudah menjadi bagian yang nyata dan hidup sekali dari rumah tangga ini, kata ndoro putri. Dan siapa yang akan mendampingi si Kedono dan si Kedini yang sudah beranjak dewasa, desah ndoro kakung, wah, sepi lho, Mbok kalau tidak ada kamu! Lagi, siapa yang dapat bikin sambel terasi yang begitu sedap dan mlekok selain kamu, Mbok, tukas Kedini dan Kedono.
Pokoknya keluarga majikan tidak mau ditinggalkan oleh Mbok Jah. Tetapi, keputusan Mbok Jah sudah mantap. Tidak mau menjadi beban sebagai kuda tua yang tidak berdaya. Hingga jauh malam, mereka tawar-menawar. Akhirnya, diputuskan suatu jalan tengah. Mbok Jah akan “turun gunung” dua kali dalam setahun, yaitu pada waktu Sekaten dan waktu Idul Fitri. Mereka lantas setuju dengan jalan tengah itu. Mbok Jah menepati janjinya. Waktu Sekaten dan Idul Fitri, dia memang datang. Bahkan Kedono dan Kedini selalu ikut menemaninya duduk nglesot di halaman masjid keraton untuk mendengarkan suara gamelan Sekaten yang hanya berbunyi tang-tung-tung-grombyang itu. Malah, lama-kelamaan mereka bisa ikut larut dan menikmati suasana Sekaten di masjid itu.
“Kok, suaranya aneh ya, Mbok. Tidak seperti gamelan kelenengan biasanya.”
“Ya, tidak, Gus, Den Rara. Ini gending keramatnya Kanjeng Nabi Muhammad.”
“Lha, Kanjeng Nabi apa tidak ngantuk mendengarkan ini, Mbok?”
“Lha, ya, tidak. Kalau mau mendengarkan dengan nikmat, pejamkan mata kalian.”
“Nanti rak kalian bisa masuk.”
Mereka menurut. Dan betul saja, lama kelamaan suara gamelan Sekaten itu enak juga didengar.
Selain Sekaten dan Idul Fitri itu peristiwa menyenangkan karena kedatangan Mbok Jah, sudah tentu juga oleh-oleh Mbok Jah dari desa. Terutama juadah yang halus, dan gurih, dan kehebatan Mbok Jah menyambal terasi yang tidak kunjung surut. Sambal itu ditaruhnya dalam satu toples dan kalau habis, setiap hari dia masih juga menyambelnya. Belum lagi dia membantu menyiapkan hidangan Lebaran yang lengkap. Orang tua renta itu masih ikut menyiapkan segala masakan semalam suntuk. Dan semuanya masih dikerjakannya dengan sempurna. Opor ayam, sambel goreng ati, lodeh, srundeng, dendeng ragi, kupat, lontong, abon, bubuk udang, semua lengkap belaka disediakan oleh Mbok Jah. Dari mana energi itu datang pada tubuh orang tua itu tidak seorang pun dapat menduganya.
Setiap dia pulang ke desanya, Mbok Jah selalu kesulitan untuk melepaskan dirinya dari pelukan Kedono dan Kedini. Anak kembar laki perempuan itu, meski sudah mahasiswa, selalu saja mendudukkan diri mereka pada embok tua itu. Ndoro putri dan ndoro kakung selalu tidak pernah lupa menyiapkan uang sangu beberapa puluh ribu rupiah dan tidak pernah lupa wanti-wanti pesan untuk selalu kembali setiap Sekaten dan Idul Fitri.
“Inggih, Ndoro-ndoro saya dan Gus-Den Rara yang baik. Saya pasti akan datang.”
Tetapi, begitulah. Sudah dua Sekaten dan dua Lebaran terakhir Mbok Jah tidak muncul. Keluarga Mulyono bertanya-tanya, jangan-jangan Mbok Jah mulai sakit-sakitan atau jangan-jangan malah …
“Ayo, sehabis Lebaran kedua, kita kunjungi Mbok Jah ke desanya,” putus ndoro kakung.
“Apa Bapak tahu desanya?”
“Ah kira-kira, ya, tahu. Wong di Gunung Kidul saja, lho. Nanti kita tanya orang.”
Dan waktu bertanya ke sana kemari di daerah Tepus, Gunung Kidul, itu ternyata lama sekali. Pada waktu akhirnya desa Mbok Jah itu ketemu, jam sudah menunjukkan lewat jam dua siang. Perut Kedono dan Kedini sudah lapar meskipun sudah diganjal dengan roti sobek yang seharusnya sebagian untuk oleh-oleh Mbok Jah.
Desa itu tidak indah, nyaris buruk, dan ternyata tidak juga makmur dan subur. Mereka semakin terkejut lagi waktu menemukan rumah Mbok Jah. Kecil, miring, dan terbuat dari gedek dan kayu murahan. Tegalan yang selalu diceritakan ditanami dengan palawija nyaris gundul tidak ada apaapanya.
“Kulo nuwun. Mbok Jah. Mbok Jah.”
Waktu akhirnya pintu dibuka, mereka terkejut lagi melihat Mbok Jah yang tua itu semakin tua lagi. Jalannya tergopoh, tetapi juga tertatih-tatih menyambut bekas majikannya.
“Walah, walah, Ndoro-ndoro saya yang baik, kok, bersusah-susah mau datang ke desa saya yang buruk ini. Mangga, mangga, ndoro sekalian masuk dan duduk di dalam.”
Di dalam hanya ada satu meja, beberapa kursi yang sudah reot, dan sebuah amben yang agaknya adalah tempat tidur Mbok Jah. Mereka disilakah duduk. Dan, keluarga Mulyono masih ternganganganga melihat kenyataan rumah bekas pembantu mereka itu.
“Ndoro-ndoro, sugeng riyadi, nggih, minal aidin wal faizin. Semua dosa-dosa saya supaya diampuni, nggih, Ndoro-ndoro, Gus-Den Rara.”
“Iya, iya, Mbok. Sama-sama saling memaafkan.”
“Lho, ini tadi pasti belum makan semua, to? Tunggu, semua duduk yang enak, si Mbok masakkan, nggih?”
“Jangan repot-repot, Mbok. Kita tidak lapar, kok. Betul!”
“Aah, pasti lapar. Lagi ini sudah hampir Asar. Saya masakkan nasi tiwul, nasi dicampur tepung gaplek, nggih.”
Tanpa menunggu pendapat ndoro-ndoronya, Mbok Jah langsung saja menyibukkan diri menyiapkan makanan. Kedono dan Kedini yang ingin membantu ditolak. Mereka kemudian menyaksikan bagaimana Mbok Jah yang di dapur mereka di kota dengan gesit menyiapkan makanan dengan kompor elpiji dengan nyala api yang mantap; di dapur desa itu yang sesungguhnya juga di ruang dalam tempat mereka duduk – mereka menyaksikan si Mbok dengan susah payah meniup serabut-serabut kelapa yang agaknya tidak cukup kering mengeluarkan api. Akhirnya, semua makanan itu siap juga dihidangkan di meja. Yang disebut sebagai sebuah makanan itu nasi tiwul, daun singkong rebus, dan sambal cabe merah dengan garam saja. Air minum disediakan di kendi yang terbuat dari tanah.
“Silakan Ndoro, makan seadanya. Tiwul Gunung Kidul dan sambelnya Mbok Jah tidak pakai terasi karena kehabisan terasi, dan temannya cuma daun singkong yang direbus.”
Mereka pun makan pelan-pelan. Mbok Jah yang di rumah mereka kadang-kadang masak spaghetti atau sup makaroni, tetapi di rumahnya sendiri ia hanya mampu masak tiwul dengan daun singkong rebus tanpa terasi. Dan keadaan rumah itu? Ke mana saja uang tabungannya yang lumayan banyak itu pergi? Bukankah dia dulu berani pulang ke desa karena sanak saudaranya akan dapat menolong dan menampungnya dalam desa itu? Keluarga itu, semakin dibentuk oleh pertanyaan batin kolektif, membayangkan berbagai kemungkinan. Dan Mbok Jah seakan mengerti apa yang sedang dipikir dan dibayangkan oleh ndoro-ndoronya, segera menjelaskan.
“Sanak saudara saya itu miskin semua kok, Ndoro, jadi uang sangu saya dari kota, lama-lama ya, habis buat bantu ini dan itu.”
“Lha, Lebaran begini apa mereka tidak datang to, Mbok?”
“Lha, yang dicari di sini apa lho, Ndoro. Ketupat sama opor ayam?”
“Anakmu?”
Mbok Jah menggelengkan kepala tertawa kecut.
“Saya itu punya anak to, Ndoro?”
Kedono dan Kedini tidak tahan lagi. Diletakkannya piring mereka dan langsung memegang bahu embok mereka.
“Kau ikut kami ke kota, ya? Harus! Sekarang juga bersama kami!”
Mbok Jah tersenyum, tetapi menggelengkan kepala.
“Simbok tahu kalau anak-anakmu akan menawarkan ini. Kalian anak-anakku yang baik. Tapi tidak. Gus Den Rara, rumah simbok di hari tua, ya, di sini. Nanti Sekaten dan Lebaran yang akan datang, saya pasti datang. Betul.”
Mereka pun tahu itu keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Lalu mereka pamit pulang. Tetapi hujan turun semakin deras dan rapat. Mbok Jah mnegingatkan ndoro kakungnya kalau hujan begitu akan susah mengemudi. Jalan tidak kelihatan saking rapatnya air hujan turun. Di depan hanya akan kelihatan warna putih dan kelabu. Mereka lantas duduk berderet di amben di beranda memandang ke tegalan. Benar, tegalan itu berwarna putih dan kelabu.
Teks cerpen B
DOA ISTRI TUKANG GORENGAN
Ch. Enung Martina
Pagi ini aku bangun seperti biasanya ketika jarum tepat di jam empat subuh. Semua penghuni rumah masih terlelap dalam mimpi mereka. Kusiapkan sarapan dan bekal makan untuk anak-anak yang akan sekolah. Seperti hari-hari biasanya sesudah beres urusan di rumah, aku pergi ke pasar tradisional untuk belanja keperluan dagangan suamiku. Suamiku seorang tukang gorengan yang mangkal di dekat terminal angkot di Tangerang.
Pasar Serpong sudah buka sejak pagi buta. Para pedagang yang berjualan di area parkir angkot sibuk melayani para pembeli yang kebanyakan para bakul yang akan berbelanja untuk dijual lagi di rumahnya atau dijajakan keliling. Kebanyakan para pembeli memang kaum hawa. Area parkir ini sampai jam enam digunakan untuk tempat mangkal para penjual sayur, buah, makanan kecil, bumbu, dan lain-lain.
Aku mulai mencari barang yang akan kubeli. Karena suamiku penjual gorengan, barang yang kubeli adalah minyak curah, tepung terigu, tepung tapioka untuk campuran tepung terigu agar rasa gorengan lebih renyah dan kemeriuk, toge, wortel, kubis, daun bawang, ubi jalar, pisang uli, singkong, dan tentu saja tahu-tempe.
Ini dia masalahnya. Sesudah aku berkeliling mencari bahan-bahan tadi ternyata semua barang harganya makin naik saja. Sementara itu uang modal kami tetap sama, tidak bertambah. Wadoohh, opo iki, rek? Semua barang kok mahal.
Harga semua barang naik terus karena harga minyak dunia makin mahal. Begitu kata orang-orang. Katanya lagi bahan makanan ikut-ikutan mahal karena pengaruh minyak dunia dan juga karena global warming. Katanya sekarang lingkungan hidup makin kacau karena itu tanaman pangan pun kena akibatnya. Kan sekarang lagi ngetren global warming. Katanya lagi segala bencana yang terjadi di muka bumi ini gara-gara satu kata asing itu. Dan yang jelas semuanya itu ulah manusia begitu katanya. Kalau global warming ya itu sih tak begitu kupahami, tetapi kalau kekacauan ini ulah manusia itu sih setuju sekali.
Jadi semua orang harus mulai memikirkan bumi ini dengan berbagai cara. Salah satunya memperhatikan polusi yang dibuat oleh kendaraan yang berbahan bakar yang asalnya dari fosil. Sisa bahan bakar dari kendaraan yang berupa asap itu mengandung CO. Katanya lagi, gas itu semua menguap ke udara sampai sangat jenuh. Lha yang menyebabkan bumi makin panas dan gonjangganjing iki sajane sopo? Kami ini kan hanya wong cilik pembuat gorengan saja. Kami „ ndak ngerti apa itu global warming, tetapi yang kami rasakan bahwa hidup semakin sulit. Jadinya yang dikatakan dalam suluk dalang waktu wayangan kok jadi kenyataan, ya? Bumi gonjang-ganjing.
Lha, kula niku naming wong cilik. Bojone tukang gorengan, yang ndak pernah baca koran. Paling dengar berita dari tv, kata mbak penyiar yang ayu-ayu itu, memang segala sesuatu lagi tidak seimbang. Nah, itu dia akibat dari semua itu menimpa kami, keluarga tukang gorengan. Tentu saja aku tidak sendirian, itu sudah lama kutahu. Kami, wong cilik ini menjadi korban pertama dari semua situasi ini.
Tapi, yang mengherankan para penggede itu kok sepertinya tidak menyadari, apa lagi peduli pada keadaan ini. Mereka masih asyik dengan mainan masing-masing yang menghabiskan milyaran rupiah. Itu kata Mas Wahyu, mahasiswa yang jadi aktivis di kampusnya. Mas Wahyu itu suka beli gorengan buatan suamiku tiap pagi sebelum kuliah.
Karena sudah siang, akhirnya kuputuskan untuk pulang ke rumah dengan belanja seadanya sesuai uang modal belanja. Kasihan Mas Karmin, akan diprotes langganannya karena harga gorengan tambah mahal. Kasihan anak-anak, uang sekolahnya akan telat lagi. Kasihan si bungsu, susunya akan tambah diencerkan dengan ditambah air banyak-banyak. Kasihan Pak Haji, uang kontrakannya akan nunggak lagi. Wah… kok, gara-gara harga minyak dan gombal warming tadi jadinya merembet ke mana-mana, ya.
Mas Karmin sudah membereskan perangkatnya. Berangkat dengan gerobaknya. Siap mangkal dengan bahan ala kadarnya. Mas Karmin orangnya jujur. Tak mau meniru temannya yang suka mencampur minyak lama yang rupane wis ora karuan dengan minyak baru. Katanya biar ngirit. Prinsip Mas Karmin itu namanya curang. Yen curang kuwi ora apik. Temannya juga mencemplungkan plastik bekas bungkus minyak ke dalam minyak yang panas. Katanya biar gorengannya kemeripik. Mas Karmin tak mau melakukannya karena itu ora becik, dosa, meracuni pangan, hukumnya dosa. Mas Karmin adalah tukang gorengan yang paling kukagumi. Dia lelaki jujur dan tentu saja dia suami yang baik. Bagiku dia adalah lelaki lelanang jagat.
Aku mengantarkan Mas Karmin sampai pintu gang. Kembali ke rumah petak kami untuk beres-beres. Ini kulakukan pada saat semua sudah beres, duduk di tikar dan bersandar di tembok sambil menyelonjorkan kaki. Si Bungsu sudah tidur, kedua kakaknya sekolah, Mas Karmin masih jualan, dan pekerjaan rumah sudah selesai. Dalam diamku aku melipat tangan dan matur kepada yang Maha Kuasa:
Gusti Allah, Yang Maha Murah,
Segala barang di pasar tak ada yang murah.
Harga tak bersahabat lagi.
Ya Allah, Engkau yang menciptakan alam raya.
Yang kaya raya.
Bantulah kami untuk bertahan dalam situasi sulit seperti ini.
Untuk memperjuangkan hidup yang sudah Engkau beri.
Meski semua barang harganya mahal, tapi biarlah iman kami tetap kuat.
Dagangan Mas Karmin tetap bisa laku agar kami bisa melanjutkan kehidupan kami. Ingatkan kami selalu untuk selalu memelihara iman di antara harga tepung, minyak goreng, sayuran, dan kedelai yang kian naik.
Engkau memahami kesusahan ini.
Mohon kekuatanmu supaya kami bisa melalui ini semua dengan sesantiasa mengucap syukur. Biarlah harapan menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa berjuang dengan penuh semangat. Amin.
Dalam diam dan tanganku yang terkatup aku melebur bersama semesta untuk sampai kepada yang Maha Tinggi melepaskan segala beban. Doaku mengambang dalam udara yang beraroma pengap, menembusnya dan menggelepar untuk sampai pada tujuannya. Aku duduk, meski dalam pengap, aku selalu punya harapan bisa melalui satu hari saja tanpa rasa khawatir. Hari esok takperlu terlalu dirisaukan, tetapi perlu dipikirkan. Karena yang aku tahu risau tak menyelesaikan kesusahan.
Bandingkan kedua teks cerpen di atas berdasarkan kaidah kebahasaan teks cerpen berupa: lima kosakata, dua gaya bahasa serta dua kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Bandingkan kedua teks cerpen di atas berdasarkan kaidah kebahasaan teks cerpen berupa: lima kosakata, dua gaya bahasa serta dua kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
....
....
Iklan
N. Faizah
Master Teacher
Mahasiswa/Alumni Universitas Suryakancana
1
0.0 (0 rating)
Iklan
Pertanyaan serupa
RUANGGURU HQ
Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860
Produk Ruangguru
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia